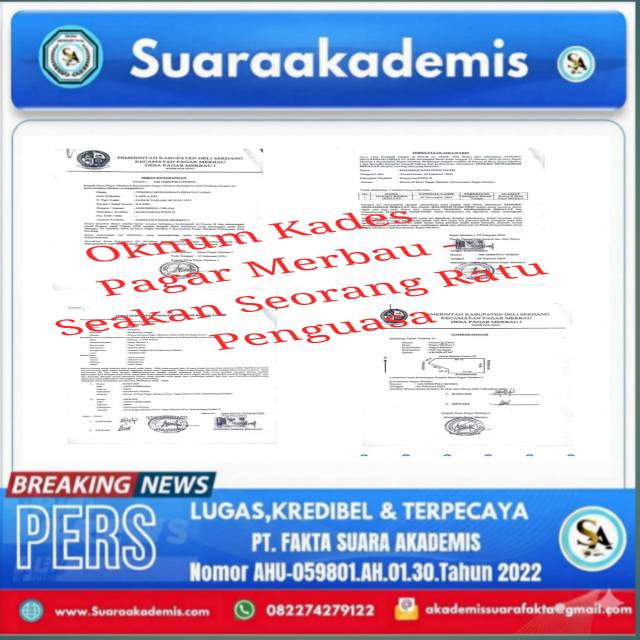Suaraakademis.com||Setiap kali diskusi tentang hutan dan deforestasi digelar, saya selalu menegaskan satu hal: apa yang saya sampaikan bukanlah opini kosong, melainkan pengalaman lapangan. Ini penting, sebab hari ini banyak orang berbicara tentang deforestasi seolah-olah itu fenomena baru, padahal pembukaan hutan—khususnya di Sumatera Timur—telah berlangsung sejak abad ke-18 hingga awal abad ke-20, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri.
Pembukaan Hutan: Bukan Cerita Baru
Sejarah mencatat, pada masa kolonial Belanda, hutan-hutan di Sumatera Timur dibuka secara masif untuk kepentingan perkebunan. Tembakau Deli, karet, kopi, teh, kakao, hingga kelapa sawit menjadi komoditas utama. Pembukaan hutan itu bukan kerja serampangan, melainkan didukung oleh pembangunan infrastruktur yang sistematis: rel kereta api, pelabuhan, hingga pemukiman buruh.
Pasca-kemerdekaan, perkebunan-perkebunan milik Belanda tersebut dinasionalisasi dan dikelola negara melalui PNP yang kemudian menjadi PTP (PTP II hingga PTP IX di Sumatera Utara). Artinya, membuka hutan bukanlah dosa tunggal. Persoalan sejatinya bukan sekadar membuka, melainkan di mana hutan dibuka, untuk apa, dan sejauh mana risiko diperhitungkan.
Pergeseran Lokasi: Dari Pantai Timur ke Bukit Barisan
Inilah titik krusial yang kerap diabaikan. Dahulu, aktivitas perkebunan dan migas terkonsentrasi di Pantai Timur—wilayah dataran rendah dengan struktur tanah yang relatif stabil. Kini, ekspansi justru bergerak ke arah dataran tinggi Bukit Barisan hingga Pantai Barat.
Padahal, Bukit Barisan merupakan kawasan yang secara ekologis sangat sensitif. Ia adalah daerah tangkapan air utama, memiliki lereng curam, berada di zona patahan gempa, serta tersusun dari tanah muda yang mudah longsor. Bahkan tanpa eksploitasi berlebihan sekalipun, kawasan ini secara alamiah sudah rawan banjir bandang dan longsor. Ketika eksploitasi dilakukan tanpa kendali, risiko itu berubah menjadi bencana yang nyaris tak terhindarkan.
Konflik Lahan: Pola Lama yang Terus Berulang
Pengalaman saya selama tiga dekade sebagai anggota Brimob (1980–2010) dalam mengamankan konflik lahan menunjukkan pola yang hampir selalu sama. Status lahan berubah: dari HPH menjadi HGU, dari HGU menjadi HTI, lalu beralih lagi menjadi kawasan tambang. Setiap perubahan status hampir pasti melahirkan konflik—baik konflik masyarakat, konflik adat, maupun konflik horizontal dan vertikal.
Ini menandakan bahwa persoalan utama bukan semata kehutanan, melainkan tata kelola. Negara sering kali hadir terlambat, atau hadir hanya dalam bentuk penerbitan izin, bukan sebagai pengendali risiko dan pelindung kepentingan publik.
Keserakahan Zaman Sekarang
Saya sering mengatakan, yang dipikirkan hari ini hanyalah keuntungan, bukan risiko. Di masa lalu, eksploitasi memang kejam—bahkan disertai kerja paksa—namun masih terdapat batas teknis dan wilayah. Kini, hampir tidak ada lagi batas. Semua bisa dibuka, alat berat semakin canggih, modal semakin besar, dan regulasi kerap bisa dinegosiasikan.
Keuntungan dinikmati segelintir pihak, sementara risiko diserahkan kepada alam dan rakyat. Ketika bencana datang, masyarakatlah yang pertama kali menanggung akibatnya.
Wilayah Rawan Bencana yang Tak Berbasis Risiko
Ironi terbesar adalah ketika wilayah yang jelas-jelas rawan bencana justru dikelola tanpa pendekatan berbasis risiko. Tata ruang dikalahkan oleh izin. Analisis dampak lingkungan sering menjadi formalitas. Saat bencana terjadi, ia disebut “musibah”.
Padahal banyak di antaranya bisa diprediksi. Bukan karena takdir semata, melainkan hasil dari akumulasi keputusan yang salah, berulang, dan dibiarkan.
Ketika Risiko Dibicarakan, Penolakan Datang
Saya masih ingat ketika berbicara tentang risiko bencana, ada yang berkata, “Bapak orang Medan, cari makan di Medan. Kami cari makan di sini.” Kalimat ini mencerminkan konflik klasik: perut versus keselamatan, jangka pendek versus jangka panjang.
Ini bukan sepenuhnya kesalahan masyarakat. Negara gagal menyediakan alternatif ekonomi yang aman. Edukasi risiko kalah oleh tuntutan kebutuhan harian. Bukan karena masyarakat tidak peduli risiko, melainkan karena mereka sering kali tidak memiliki pilihan lain.
Penutup
Banjir dan longsor yang terjadi hari ini bukan semata karena hujan deras. Ia adalah konsekuensi dari hutan yang dibuka di tempat yang salah, dengan cara yang salah, tanpa perhitungan risiko, lalu akibatnya diserahkan pada takdir.
Jika kita ingin selamat, maka tidak ada pilihan lain selain belajar dari sejarah dan menghentikan kesalahan yang sama.
Mari kita jaga alam, agar alam menjaga kita.