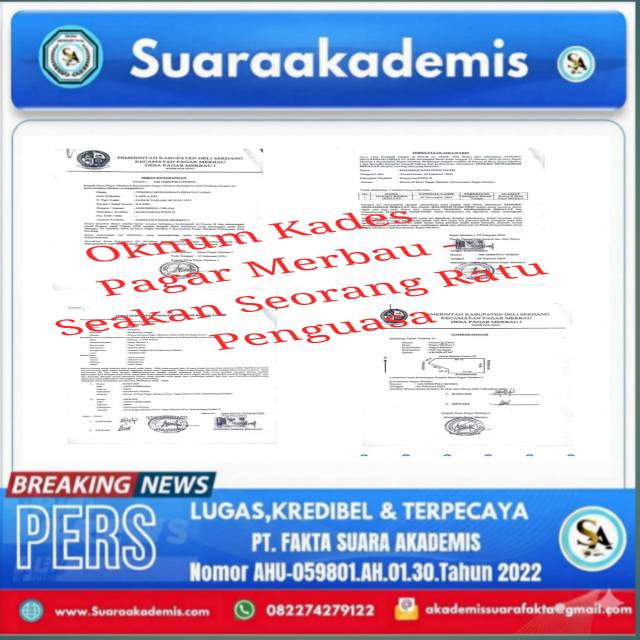Suaraakademis.com||Aceh Tamiang — Malam itu, hujan turun tanpa jeda. Tidak ada tanda, tidak ada peringatan. Sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan perlahan berubah menjadi ancaman. Saat air mulai meluap dan memasuki rumah-rumah warga, kepanikan pun tak terelakkan. Dalam hitungan jam, banjir merenggut rasa aman yang selama ini mereka genggam.
Di sudut desa, seorang ibu hanya bisa memeluk anaknya erat-erat. Matanya kosong menatap air cokelat yang menggenangi lantai rumah. Perabotan hanyut, pakaian basah bercampur lumpur, dan buku-buku sekolah anaknya tak lagi bisa diselamatkan. “Yang penting kami selamat,” ucapnya lirih, menahan tangis yang sejak tadi tak terbendung.
Bagi warga Aceh Tamiang, banjir bukan sekadar genangan air. Ia adalah kisah tentang kehilangan—kehilangan tempat berteduh, kehilangan hasil panen yang menjadi tumpuan hidup, bahkan kehilangan harapan yang dibangun bertahun-tahun. Sawah yang semula hijau kini berubah menjadi lautan air keruh. Jerih payah berbulan-bulan lenyap dalam satu malam.
Anak-anak terpaksa berhenti sekolah sementara. Seragam mereka basah, sepatu hanyut, dan buku pelajaran rusak. Namun yang lebih menyedihkan, semangat mereka ikut tenggelam bersama derasnya arus. Di pengungsian sederhana, mereka belajar memahami arti sabar di usia yang seharusnya penuh tawa.
Para lansia duduk terdiam, menatap kejauhan. Rumah yang mereka bangun sejak muda kini tak lagi ramah. Setiap sudut menyimpan kenangan, namun kini dipenuhi lumpur dan air mata. Mereka bertanya dalam hati, sampai kapan musibah ini akan terus berulang?
Meski demikian, di tengah kesedihan yang mendalam, secercah harapan masih menyala. Warga saling membantu, berbagi makanan seadanya, menguatkan satu sama lain. Relawan datang membawa uluran tangan, menjadi pengingat bahwa mereka tidak sendiri menghadapi cobaan ini.
Banjir Aceh Tamiang bukan hanya bencana alam, tetapi juga ujian kemanusiaan. Di balik angka dan data kerusakan, ada tangis ibu, kegelisahan anak, dan doa-doa yang dipanjatkan dalam sunyi. Mereka tidak meminta banyak—hanya ingin hidup tenang tanpa harus terus berdamai dengan rasa takut setiap kali hujan turun.
Semoga air segera surut, luka perlahan sembuh, dan Aceh Tamiang kembali berdiri. Sebab di tanah ini, ada banyak hati yang lelah namun tetap berharap esok hari akan lebih baik.